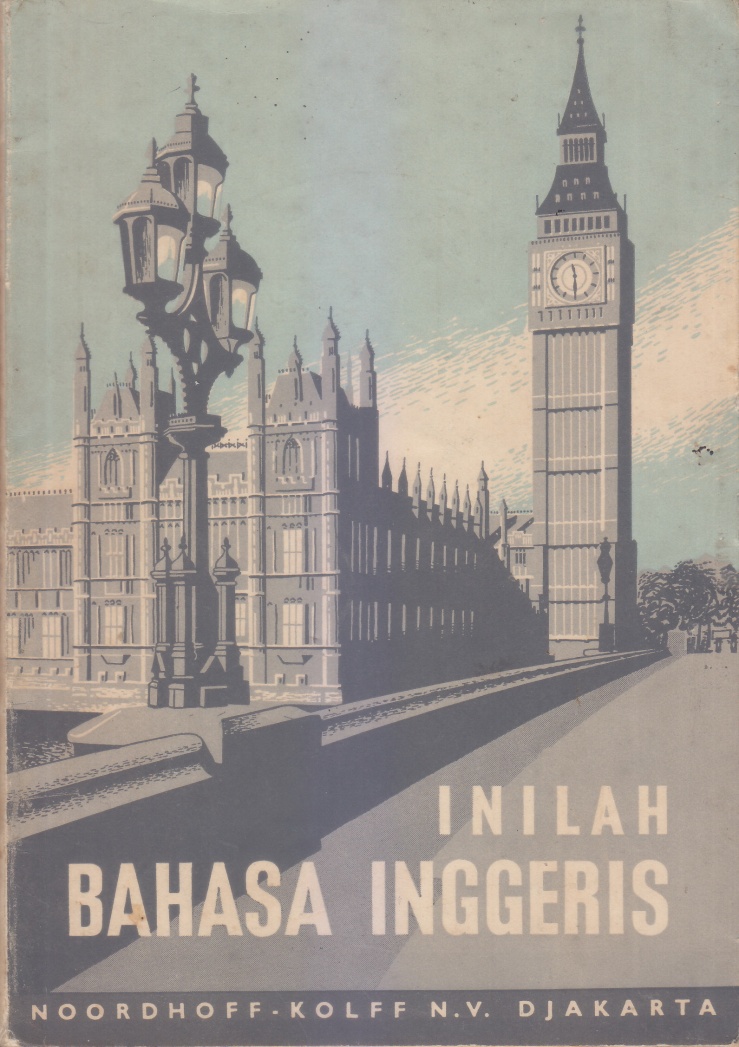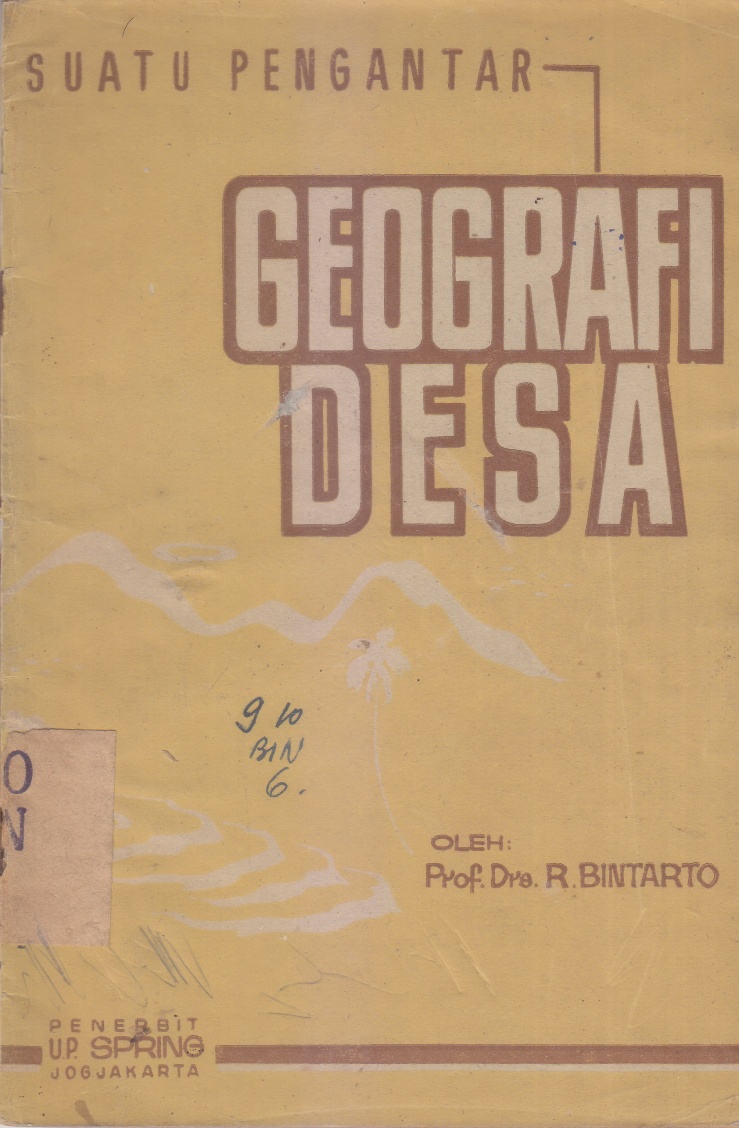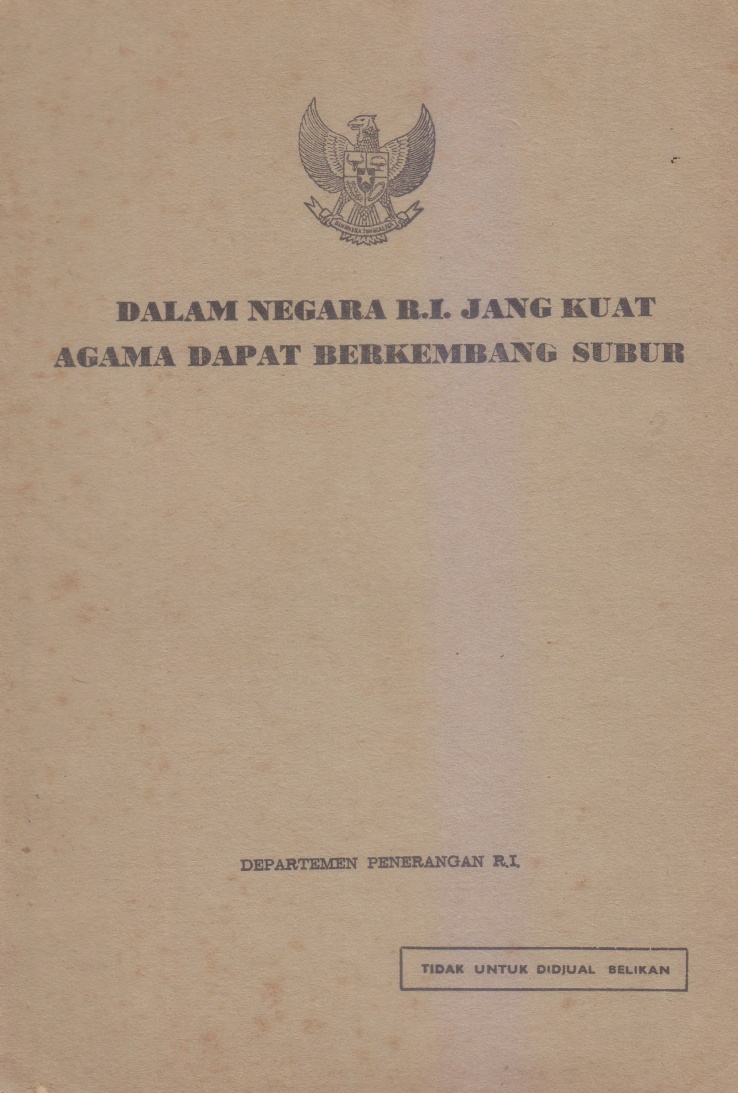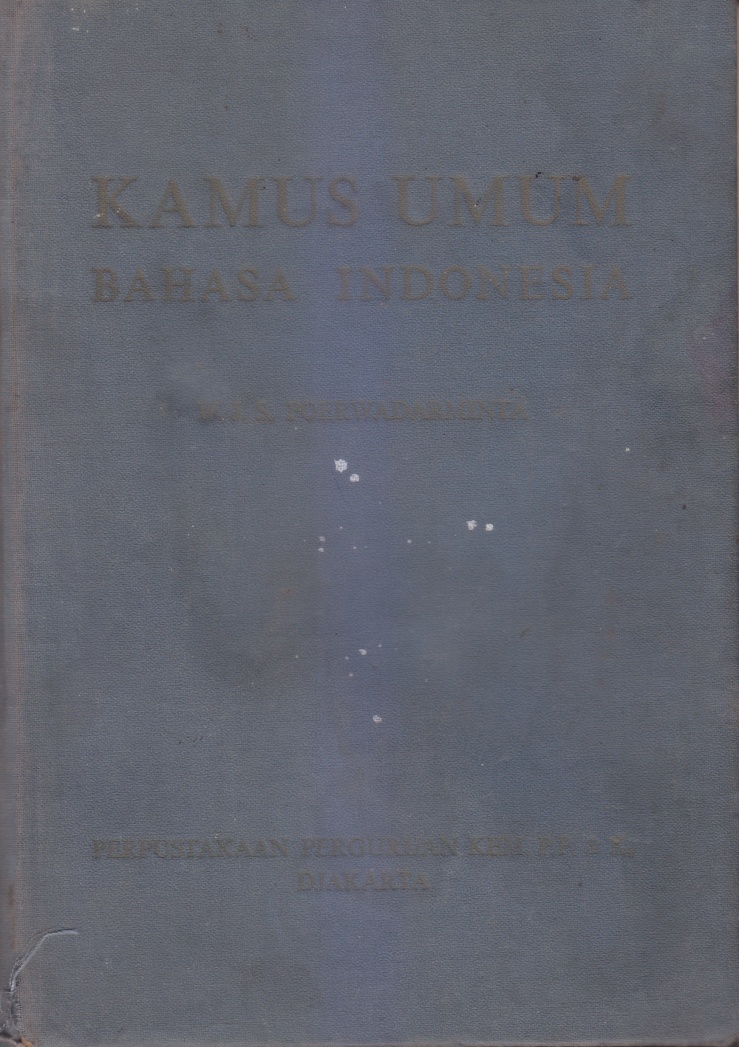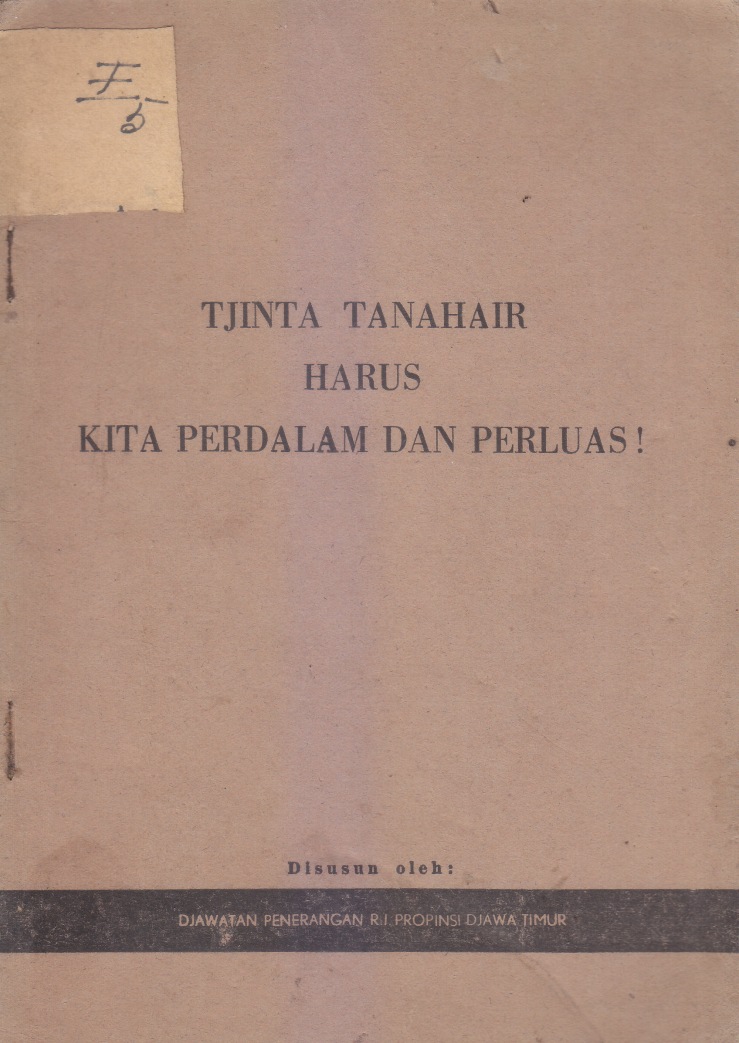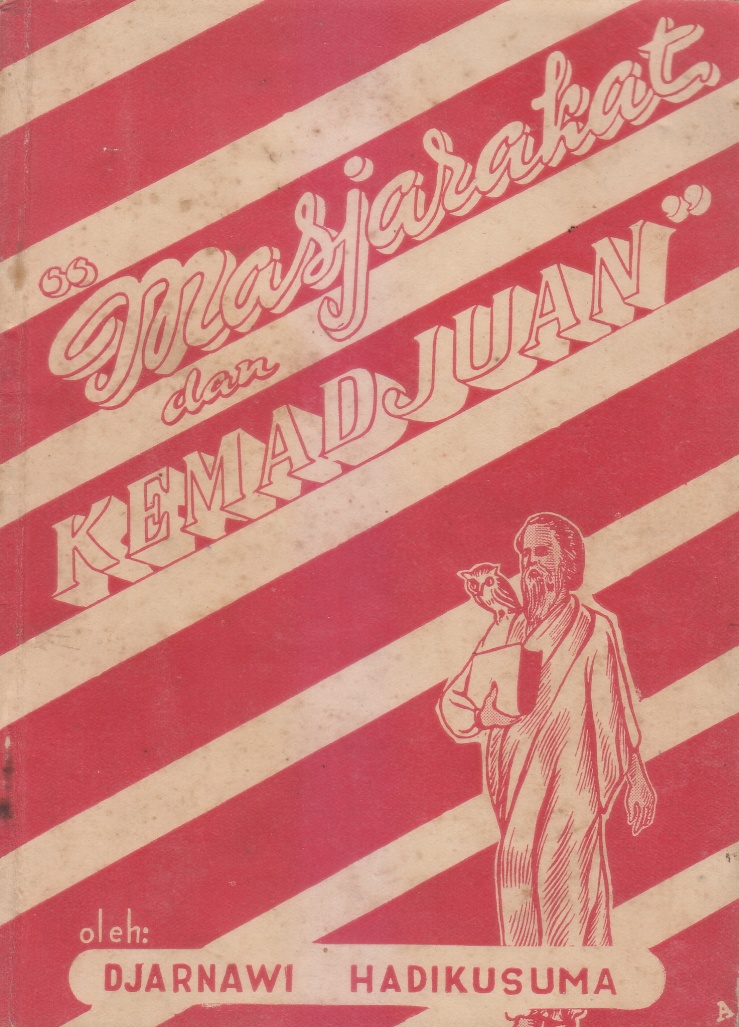Di sekolah, murid-murid duduk dan memberi perhatian saat pelajaran agama. Indonesia memiliki kebijakan agama menjadi “pelajaran” dengan nilai, menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Murid sempat bingung untuk memastikan serius belajar agama, matematika, bahasa Inggris, atau seni. Guru selalu berucap bahwa semua pelajaran penting. Murid ke sekolah untuk pintar tapi harus berakhlak. Nah, pelajaran agama dimaksudkan membentuk murid berakhlak. Pintar bersendi iman dan takwa. Di Indonesia, pelajaran agama itu penting meski orangtua sulit mencari lembaga bimbingan belajar mengadakan les agama. Pihak sekolah pun jarang mengadakan jam tambahan jam pelajaran agama, menjelang hari-hari ujian. Situasi berbeda terjadi di madrasah. Pelajaran agama bersaing dengan pelajaran umum. Kita agak “salah” membuat perbedaan “agama” dan “umum”.
Pada 1970, terbit buku berjudul Peladjaran Agama Islam susunan Utadz Dja’far Amir. Penulis memiliki sebutan ustadz, dicantumkan di buku untuk memberi kepastian murid membaca buku dari orang mengerti agama. buku terbitan AB Sitti Samsijah, Solo, tipis dan berkertas buram. Tebal 32 halaman. Murid takjub melihat gambar di sampul: Pak guru berpeci, dua murid perempuan berkerudung, dan murid lelaki tanpa peci. Mereka melihat ke papan tulis. Suasana belajar di gambar tampak modern. Pembaca mungkin kagum pada pak guru: berpenampilan rapi dengan baju berdasi dan dua pulpen di kantong. Pak guru sadar kemajuan, ingkar dari kolot.
Belajar agama, belajar akhlak. Di halaman 14-17, Ja’far Amir memberi cerita dan penjelasan tentang akhlak. Murid diharapkan mempelajari sungguh-sungguh, bukan celelekan. Pelajaran penting: “Berbitjara jang sopan itu menundjukkan bahwa orang jang berbitjara tadi betul-betul mepunjai sopan santun dan mempunjai perangai jang baik.” Kita mengandaikan “berbitjara jang sopan” mewujud pada masa sekarang. Orang-orang politik dan kaum goblok di media sosial tentu malu menggunakan bahasa jelek dan kasar. Mereka berhak mengejawantahkan iman dan takwa dengan bahasa-kesopanan dalam menanggapi pelbagai hal: menjauhi fitnah dan pamer komentar sembarangan. Wah, kalimat-kalimat bernasihat!
Kita belajar lagi jadi sopan dan berani. Isi buku Peladjaran Agama Islam mengenai berani: “Sifat berani itu selain memang sangat terpudji, djuga orang jang berani itu sangat disegani. Disegani oleh kawan maupun lawan. Sebaliknja, sifat penakut adalah sifat jang rendah. Pribadi orang jang penakut itu mendjadi merosot dalam pandangan Tuhan maupun masjarakat.” Kita bertepuk tangan membuktikan orang-orang Indonesia adalah pemberani. Berita-berita di televisi dan koran sering memberitakan orang “berani” dalam segala hal: politik, bisnis, kriminalitas, gosip, sepakbola, seni, pelesiran, dan makanan. Orang-orang “berani” bodoh, macet, boros, mubadzir, dan hina. Waduh, sebutan “si pemberani” malah ganti arti! Sekian tahun berlalu, kita malah pernah dikejutkan bahwa buku-buku pelajaran agama membuat murid jadi fanatik. Kita tak melarang fanatik tapi sadar ada doktrin bermusuhan dan menampik toleransi. Buku tentu berdampak buruk. Begitu.