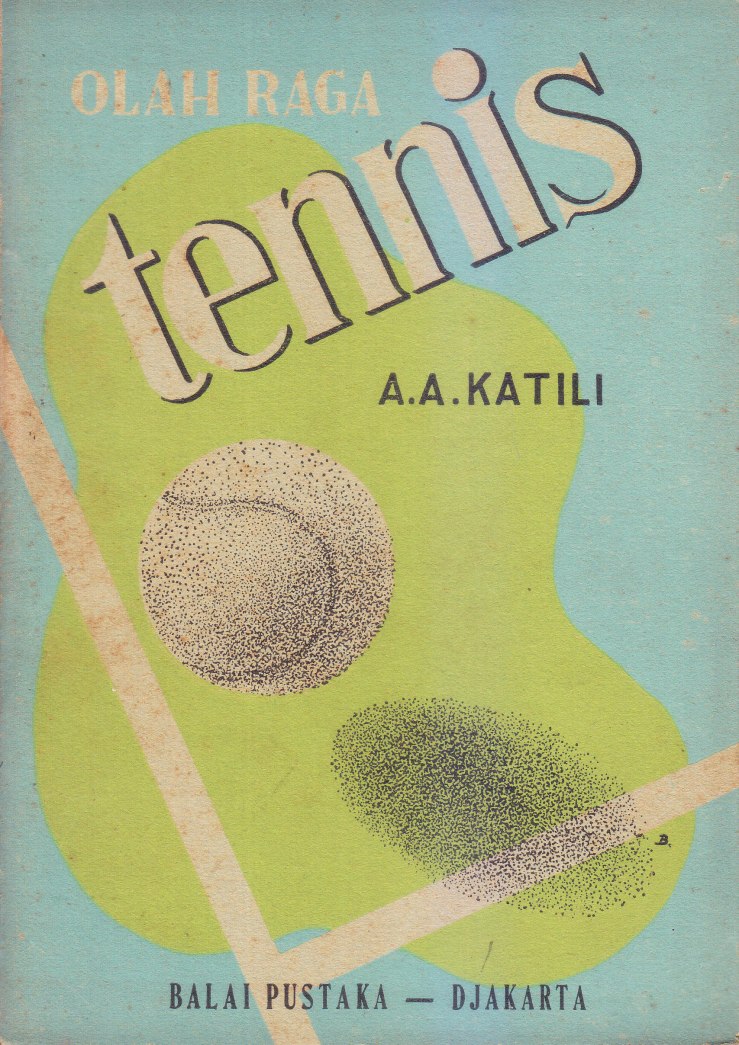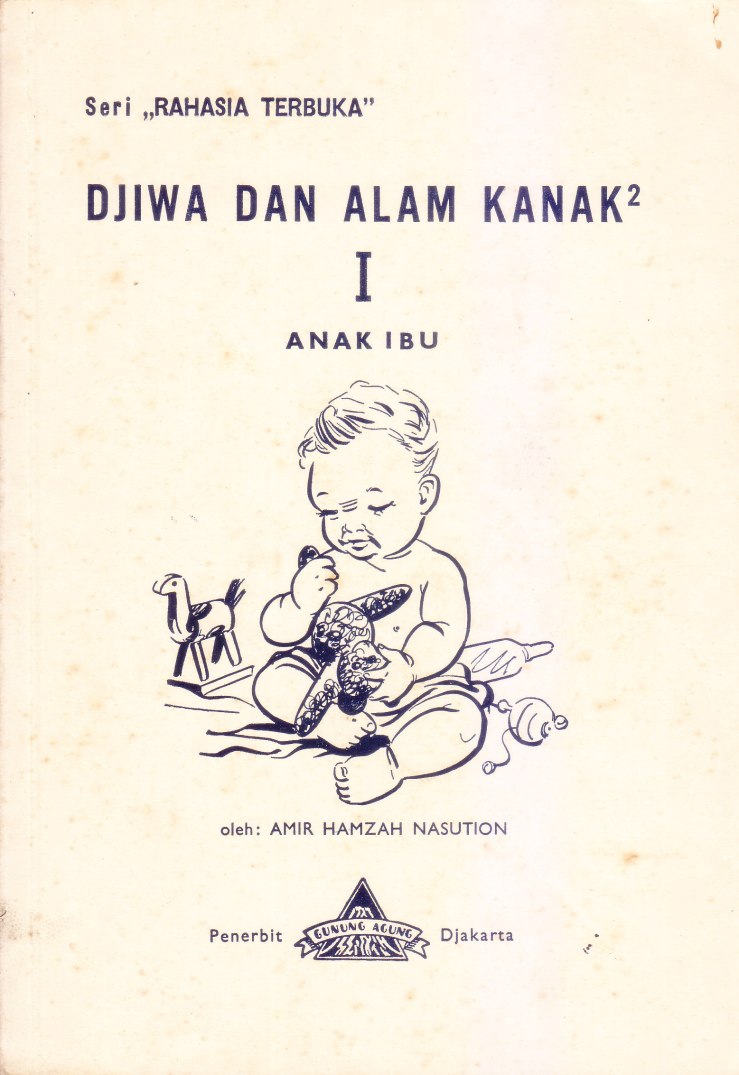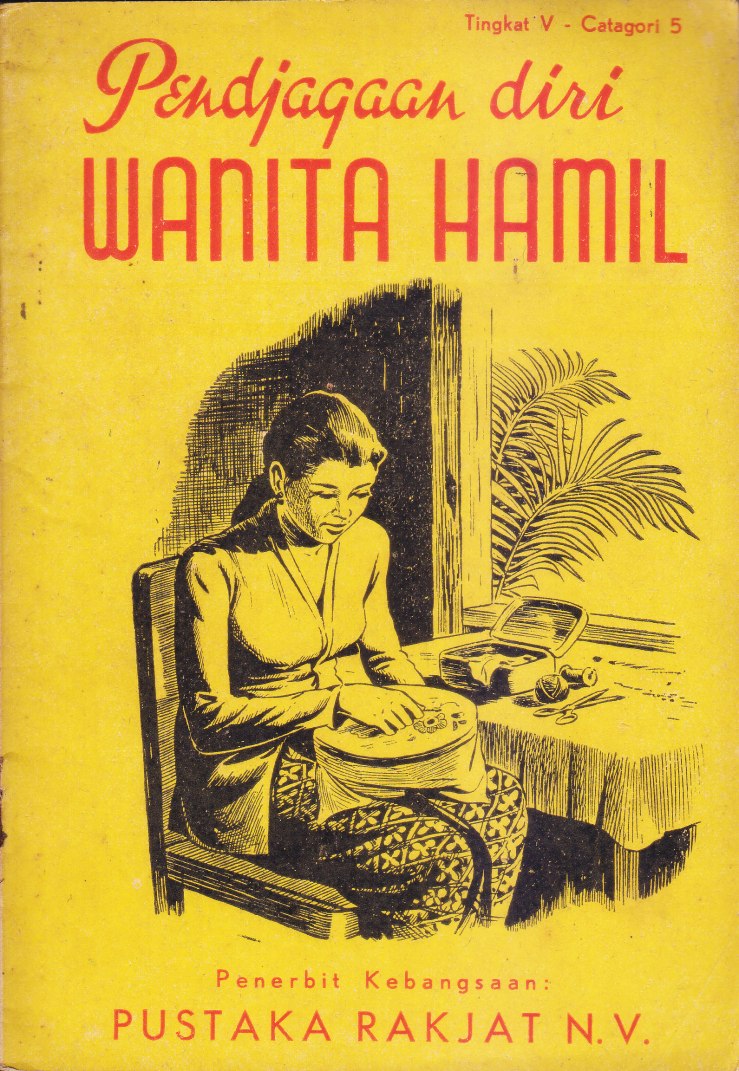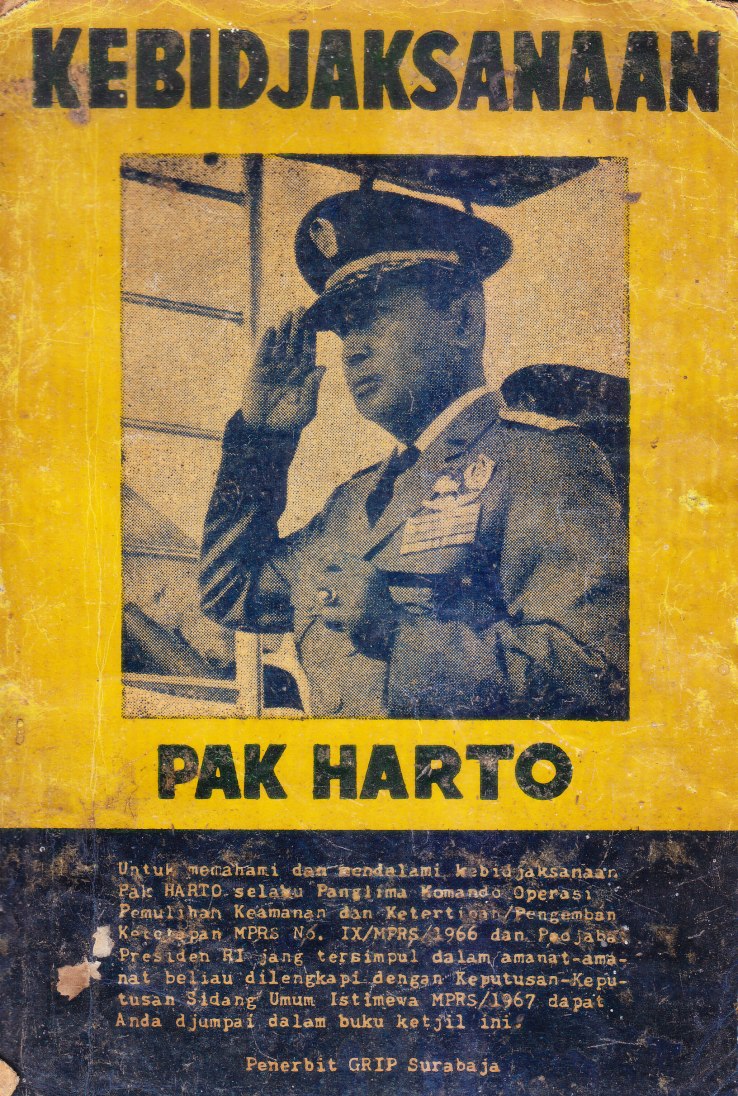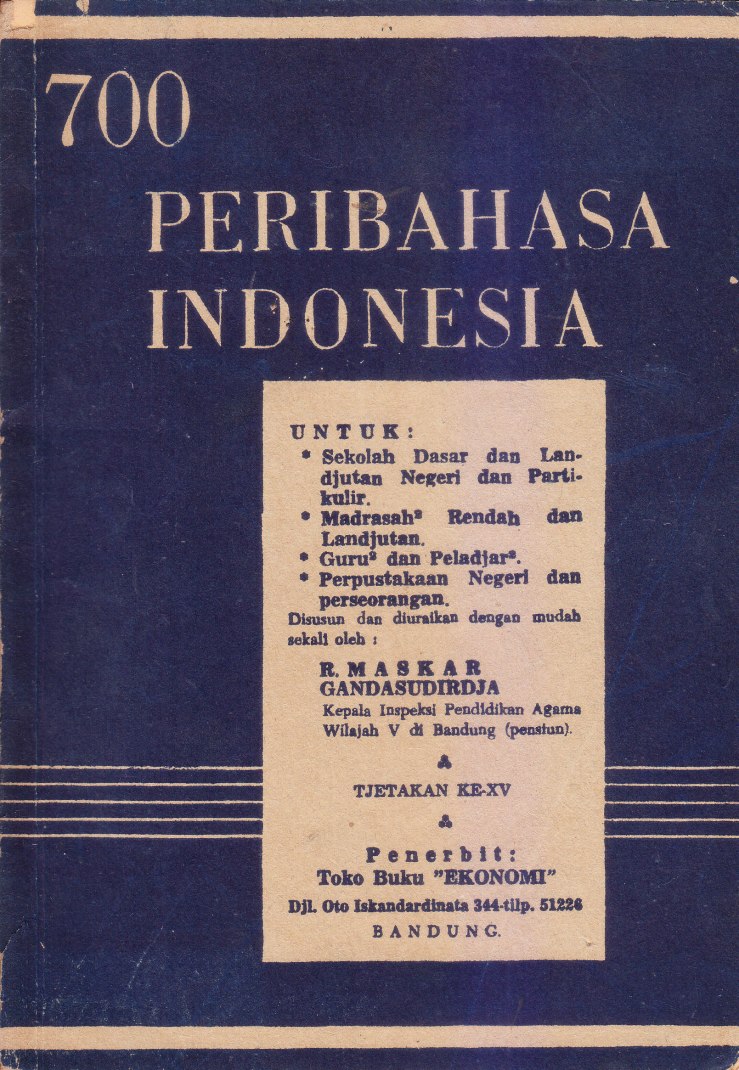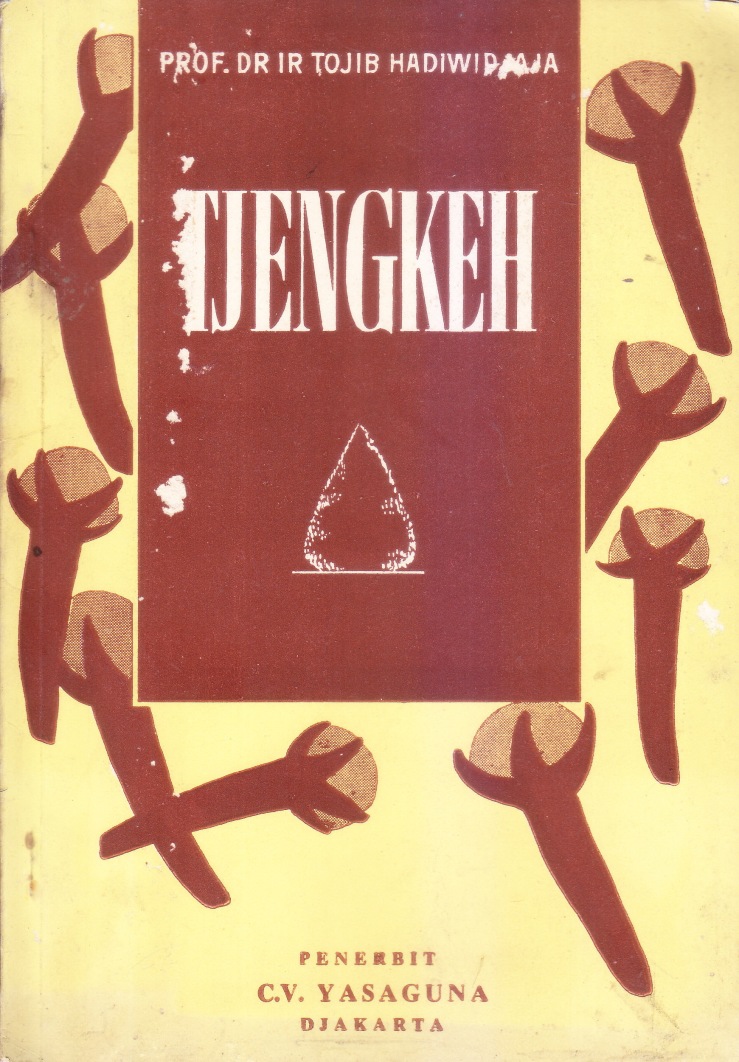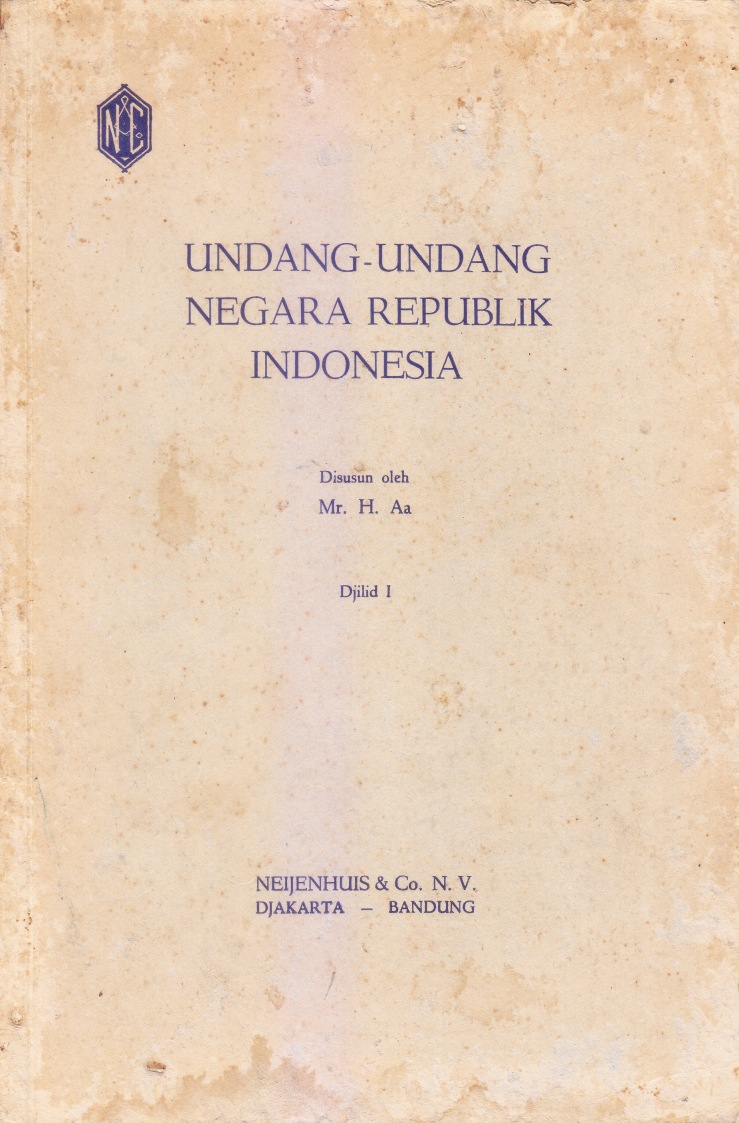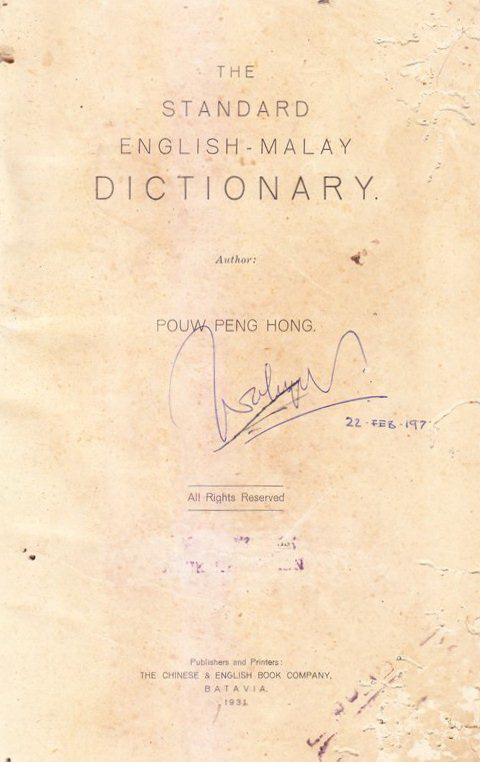Para tokoh pergerakan politik kebangsaan memiliki pilihan olah raga beragama. Mereka tak menghabiskan usia dengan pidato atau rapat. Olah raga diperlukan agar sehat. Jong Java dan Jong Sumatranen Bond memiliki program mengajak para anggota berkeringat dengan sepakbola. Sekian orang memilih olahraga berbeda: bulu tangkis dan tenis. Sejak masa kolonial, tenis menjadi olahraga “terhormat” meski tak setenar sepakbola. Bulu tangkis mulai berkembang pesat pada masa 1930-an. Kita cuma ingin mengenang tenis, berharap membuka ingatan masa lalu memuat cerita tetesan keringat di lapangan.
Tenis terus jadi kegemaran bagi orang berduit untuk membeli raket, busana, dan sewa lapangan pada masa 1940-an dan 1950-an. AA Katili mencatat perkembangan itu dengan menulis buku berjudul Olah Raga Tennis, diterbitkan oleh Balai Pustaka, 1952. Cetakan pertama pada 1944. Siapa Katili? Oesman Sastroadmidjojo memberitahukan: “Dunia tennis Indonesia mengetahui siapa Katili itu. Bekas djuara PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia) untuk tahun 1940 dan djuara Djakarta tahun 1943 ini, dengan membuat buku tennis ini membuktikan, bahwa ia tidak hanja pandai mempergunakan racketnja, tetapi djuga tjakap memakai penanja. Ia mengerti betul, apa jang dibutuhkan kaum penggemar tennis.” Konon, buku garapan Katili adalah buku pertama tentang tenis di Indonesia. Sebutan pertama untuk buku berbahasa Indonesia. Dulu, kaum penggemar tenis mungkin sudah membaca dulu buku-buku berbahasa Belanda atau Inggris.
Sejarah tenis bermula dari Prancis. Katili membahasakan: “Pada tahun 1874 permainan ini buat pertama kali dimainkan dibawah langit atas andjuran Major Wingfiled…” Penjelasan “di bawah langit” terkesan puitis ketimbang dimainkan di atas lapangan. Tenis dipaksa memiliki hubungan erat dengan langit. Barangkali para pemain awal ingin mendapat restu Tuhan. Tahun demi tahun berlalu. Tenis sampai ke Indonesia. Orang-orang bermain tenis di bawah langit Indonesia saat masih dijajah Belanda. Sebutan orang-orang itu tak harus Jawa, Sunda, Batak, atau Bugis. Keterangan dari Katili: “Dahulu jang bermain tennis di Indonesia hanja orang-orang Tionghoa, Djepang, dan Eropah. Orang Indonesia sendiri sedikit sekali, karena mahalnja alat-alat itu mendjadi rintangan jang amat besar.”
Tenis di dunia telah dipertandingkan dengan hadiah-hadiah besar. Para pemain dari pelbagai negara bersaing merebut kejuaraan tenis. Nama mereka tenar, negara pun terhormat. Pada awal abad XX, Amerika memiliki pemain-pemain hebat. Di Asia, pemaian-pemain Jepang dianggap memiliki kekuatan tak kalah dari pemain Eropa dan Amerika. Siapa ingin bertanding dan menang harus memiliki modal besar. Katili menganjurkan: “Tetapi tiap-tiap pemain sebelum bertanding haruslah mengharap supaja permainan akan lebih kuat kelak dari jang sudah-sudah. Seperti djuga dalam peperangan tiada baik kalau lasjkar-lasjkar lebih dulu sudah akan merasa kalah, sebelum bertempur, sebelum mengukur kekuatannja dengan kekuatan lawan.” Suasana perang mempengaruhi penulisan tentang tenis. Di bawah langit, bermain tenis ibarat perang.
Perkembangan tenis di Indonesia lambat. Kita memiliki cerita besar saat Yayuk Basuki rajin mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Indonesia mulai tercatat di daftar peringkat dunia, tak pernah di nomor satu atau dua. Kini, pemain tenis terkenal itu berpolitik di bawah atap gedung parlemen. Tenis pun semakin digemari meski belum akrab dimainkan di bawah langit pedesaan. Begitu.