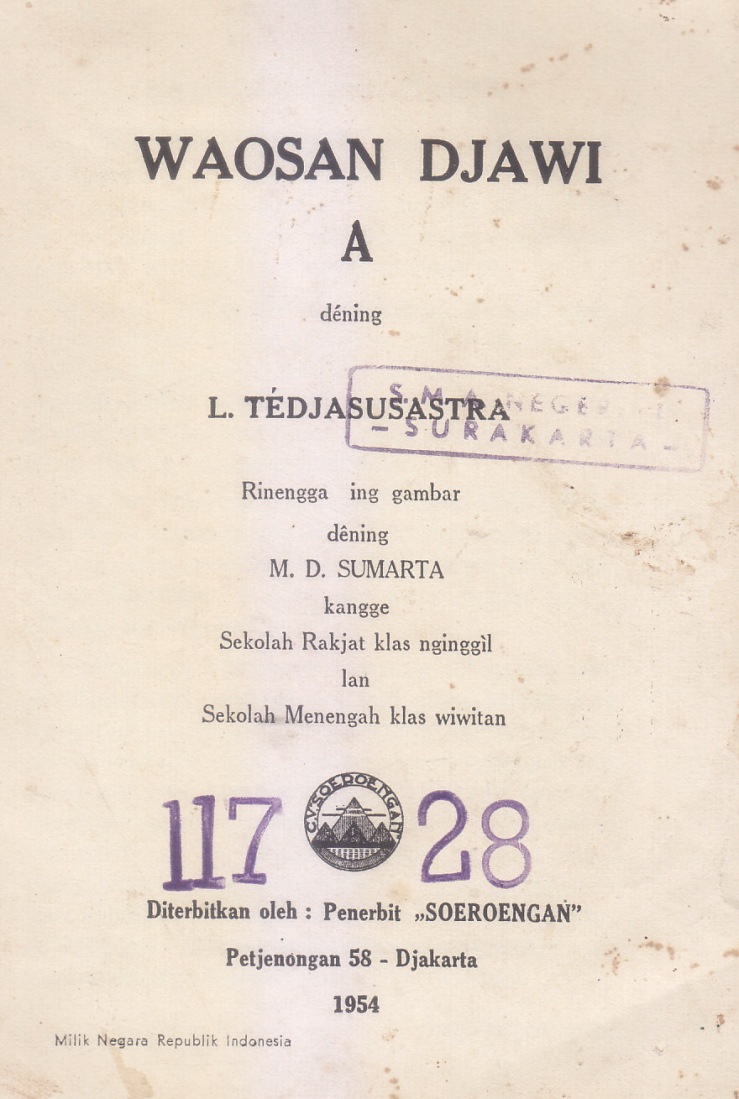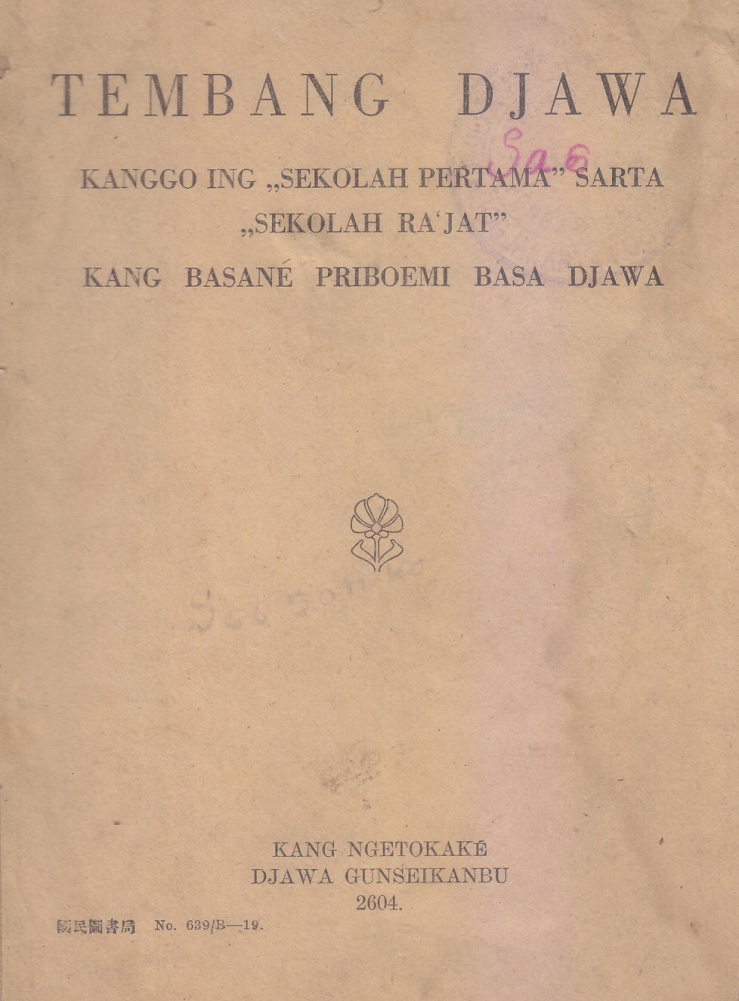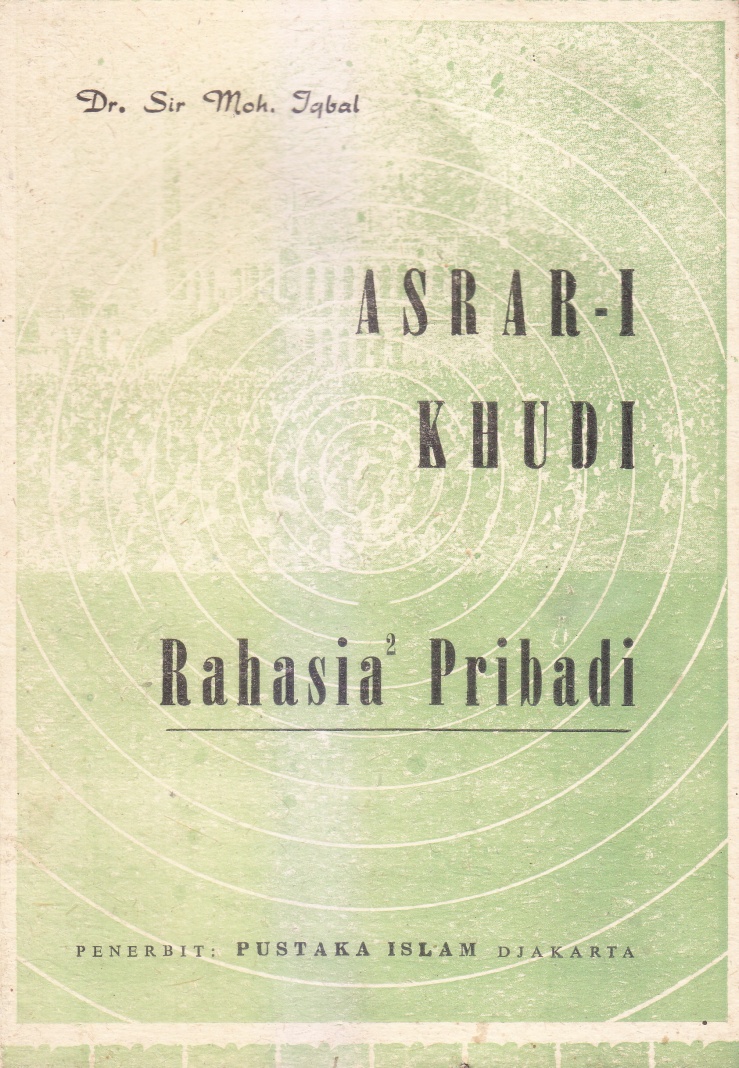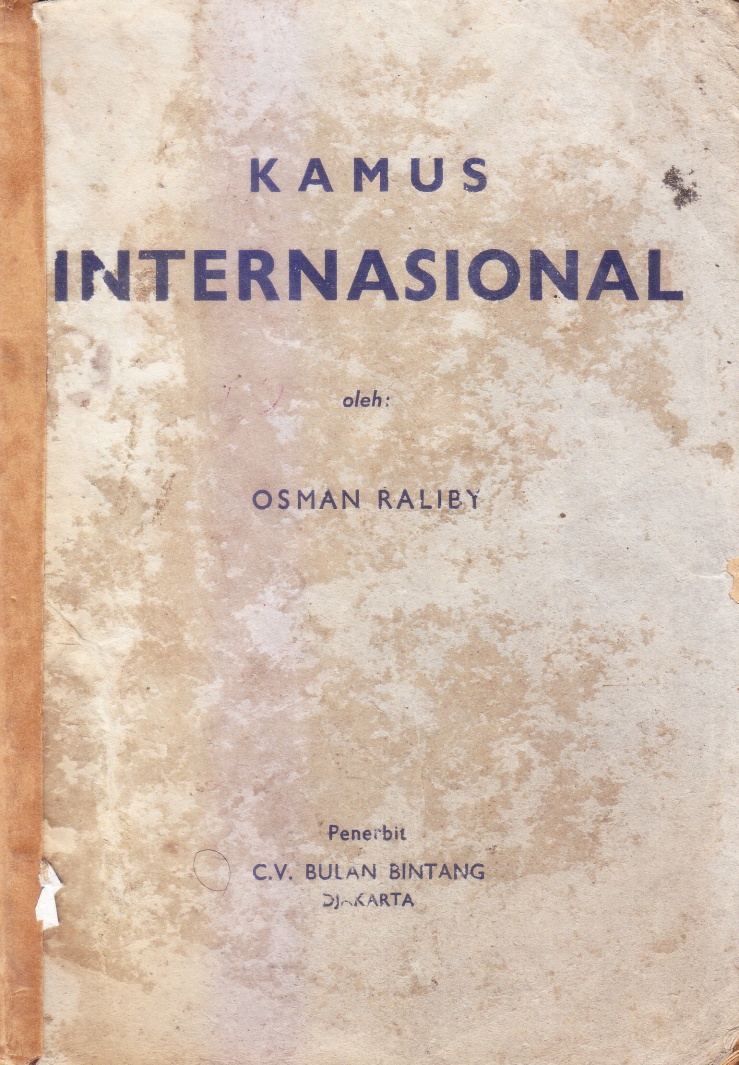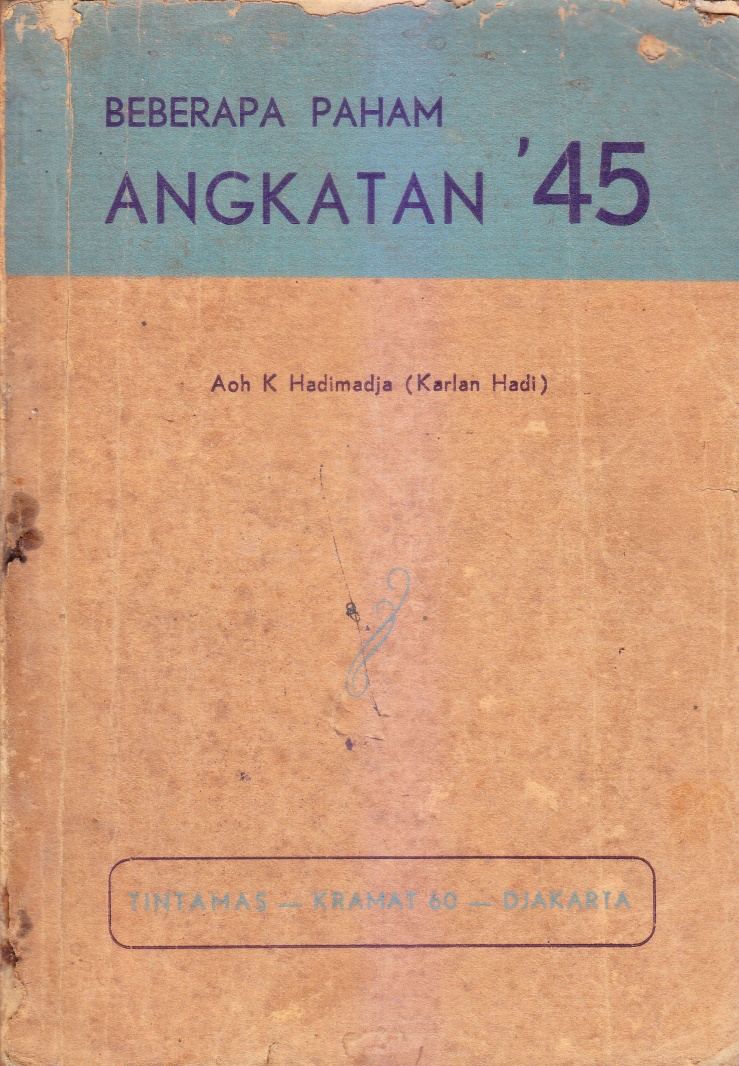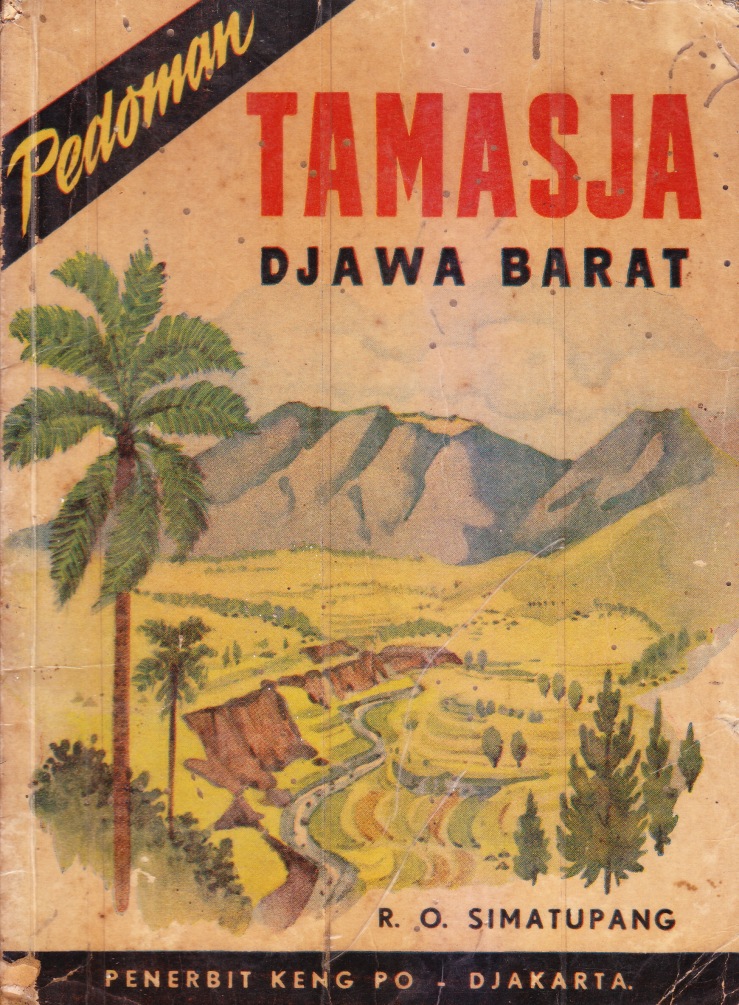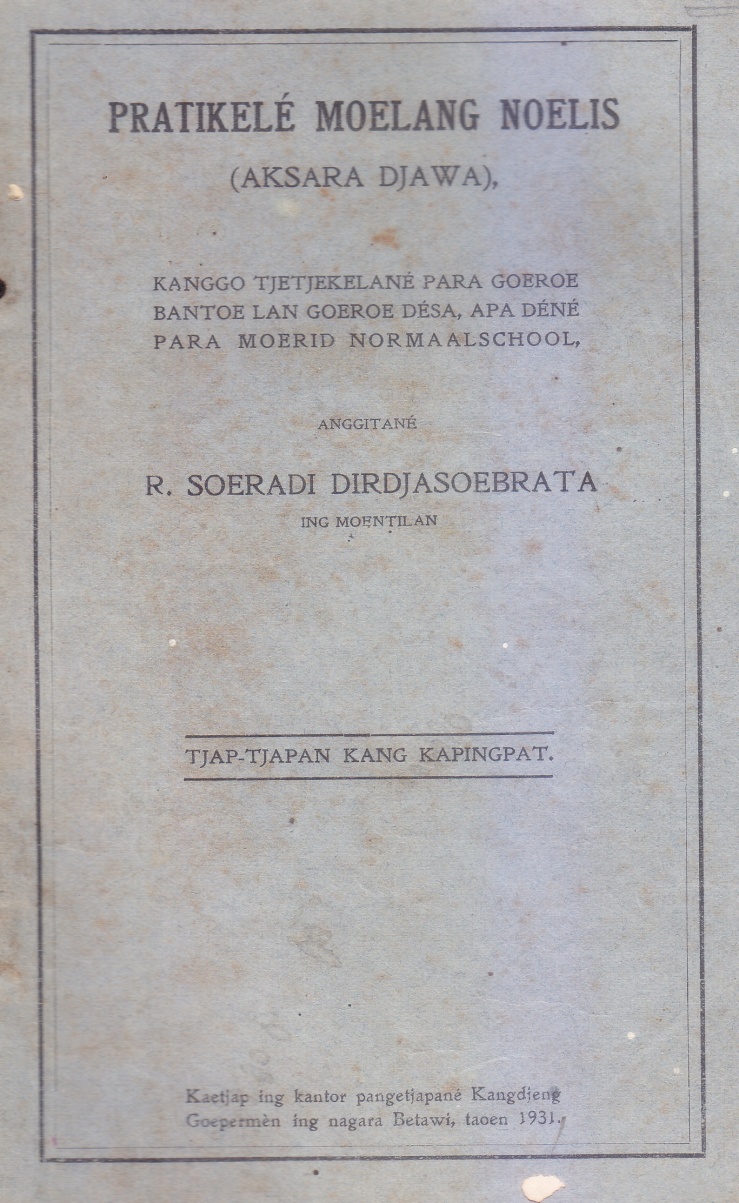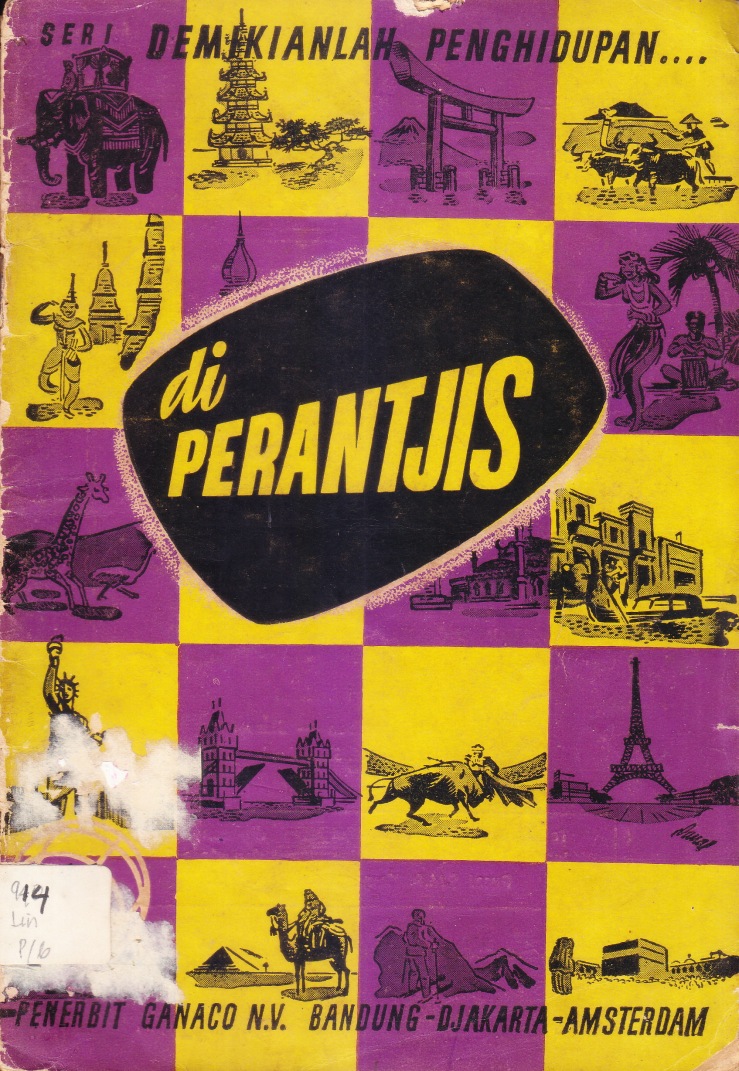Orang hidup di dunia bertugas sebagai pembaca. Siapa tak mau jadi pembaca? Orang seperti itu tetap hidup meski tak putus dirundung bebal. Siapa takut membaca? Orang itu bakal masuk ke neraka kebodohan. Siapa girang membaca? Orang itu dilarang untuk dihinakan meski jelek, miskin, dan pemilik panu-kadas-kudis-kurap. Pembaca anggaplah orang menunaikan janji hidup agar tak sia-sia. Konon, hidup cuma sekali tapi pantas digunakan membaca ribuan buku, sebelum mata terpejam dalam damai.
Pada 1954, penerbit Soeroengan (Jakarta) mengeluarkan buku berjudul Waosan Djawi garapan L Tedjasusastra. Gambar-gambar oleh MD Sumarta. Tebal 160 halaman. Waosan itu bacaan. Buku untuk bacaan bocah-bocah. Dulu, bocah tak dibiarkan dolan sepanjang hari. Melamun 12 jam. Tidur ngorok setengah hari. Belajar di sekolah dari pagi sampai malam. Hari-hari mereka memiliki arti dengan bacaan. Di Jawa, bocah-bocah itu mendapat menu bacaan berbahasa Jawa. Tedjasusastra menerangkan: “Menggah isi tuwin dapukanipun sasaged-saged sampun katata lan kalaresaken kalijan djaman lan kwontenan punika.” Sejak dulu sampai sekarang, “zaman” dijadikan patokan. Zaman ingin menangan.
Di halaman 31, bacaan berisi penjelasan-penjelasan tentang pangan. Kita telanjur meremehkan dan lupa ilmu pangan setelah jadi pembeli paling bernafsu untuk jenis-jenis olahan, sajian, dan kemasan pangan mutakhir bercap “internasional.” Pengertian agak terpendam dalam ingatan. Tedjasusastra menulis: “Wong mangan (madang) wajah esuk diarani sarapan, wajah sore diarani kanggo mantjal kemul, lah bareng madang wajah awan apa jenenge? Apa anten krama? Lumrahe wong madang sedina ping telu, esuk, awan, sore, lumrahe sing akeh dewe jen awan.” Penjadwalan dan jenis makanan mulai jadi bisnis restoran, rumah makan, dan warung. Iklan-iklan mereka menggantikan ilmu pangan dari para leluhur.
Bacaan berisi nasihat bijak ada di halaman 117-120. Bacaan berjudul “Mahasiswa lan Nini-Nini.” Guru bercerita pada murid-murid: “Ana setuden, kesed, wegahan, senengane mung blajangan ora tau mlebu sekolah. Grengseng lan gregete sinau wis ora ana, pangarep-arep wis entek, malah wis mupus arep metu golek pagawean saoleh-olehe.” Wong goblok alias pekok itu mengalami kejadian aneh saat bertemu dengan perempuan tua. Kesadaran perlahan muncul setelah melihat adegan simbah. Mahasiswa itu berkata: “Nuwun, mbah, keparenga njuwun priksa, paku mok dipun asah makaten punika bade kangge punapa.” Jawab lugu dan lugas dari simbah: “O, anu, ngger, bade kula damel dom.” Mahasiswa gumum dan sangsi. Simbah pun mengatakan: “Saged, ngger, uger kanti sabar lan tlatos tur boten wegahan, wani rekaos, mesti saged dados.” Kita biasa mengetahui orang membeli dom memuat tulisan “made in China”. Simbah bukan konsumen semugih. Simbah memilih membuat dom dari paku. Usaha itu membuat mahasiswa malu dan malu.
Di halaman 135-139, cerita berjudul “Tidak Bermuka Ramah Tamah Djangan Membuka Toko”, bertokoh Giok Sing. Cerita berlangsung di Solo. Tokoh itu bekerja keras sejak bocah untuk meraih sukses. Bocah dalam nestapa tapi menjadi orang dagang setelah rajin belajar dan sanggup mewujudkan mimpi indah. Pesan dalam bacaan: “Giok Sing jakin jen wong dagang iku kudu duwe pengalaman, sregep lan wani rekasa. Kadjaba iku kudu prigel lan tjak-tjek bisa nggemeni wektu, apa maneh ora kena ninggal petung.” Nasihat itu berguna bagi orang-orang di Jawa agar berani jadi orang dagang atau bertoko. Begitu.